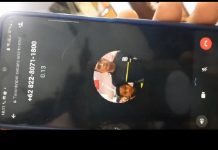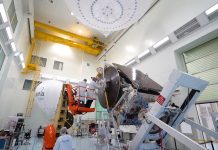Oleh: Suparto Wijoyo
Esais, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
SELURUH mata dunia kini tertuju kepada derita etnis Rohingya yang berdiam diri tanpa status kewarganegaraan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Pembunuhan, pembantaian, teror dan ancaman terencana terus digulungkan melingkupi nasib yang secara teologis beriman dalam genggam Islam. Konflik yang menyembul mengepung jazirah Rohingya tak pelak bereskalasi memasuki ruang-ruang agama. Keluasan dan kedalaman nestapa diaduk sedemikian rupa menghias cakrawala Asia Tenggara dengan noda kemanusian yang tidak terperikan. Beratus tahun kisah sedih itu terlukis memahat babakan lakon hidup warga muslim Rohingya yang berdiam mendekam memenuhi anugrah Tuhan di Arakan sejak 1799. Berbagai referensi memberikan pekabaran yang beragam meski dengan kosa kata tunggal: ada umat Islam di Rakhine, Myanmar.
Perseteruan ditanam dan dirabuki para kolonialis termasuk Inggris yang datang menyerang di tahun 1824-1942 dalam ekspansi pendudukan Burma. Migrasi pekerja disesakkan ke Burma untuk kepentingan imperialisme Barat. Pada 1942 semua terbelalak dengan kedigdayaan Jepang yang mampu menginvasi Burma dalam pralaya Perang Dunia II. Muslim Burma terserang dan berada dalam sengatan yang menikam dari gelora Perang Asia Timur Raya. Purnama menjelang dan gerhana nasib hitam terungkap dengan Pemerintahan Perdana Menteri U Nu yang memberikan lembar pengabsahan kewarganegaraan orang-orang Rohingya di Rakhine, tepatnya di bagian wilayah Mayu. Meski demikian, ternyata nasib tetap berselancar tersiar tidak nyaman dalam remang zaman.
Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pada masa kudeta kekuasaan beralih ke tangan Jenderal Ne Win dengan otoritas Partai Sosialis Burma, diberlakukanlah Pakta Darurat Keemigrasian di tahun 1962-1974 sebagai dasar hukum untuk mengusir etnis Rohingya. Tahun 1977 Operasi Naga Min dilancarkan dengan memaksa etnis Rohingya meninggalkan tanah airnya ke wilayah Bangladesh sampai adanya tekanan Liga Muslim agar mereka kembali di tahun 1979. Pada tahun 1982 pengusiran kembali terjadi dalam skala yang lebih serius dalam rentang panjang dengan fluktuasi deritanya dari tahun 1991 sampai kini tahun 2017.
Masyarakat internasional nyaris tidak habis pikir bahwa di abad ke-21 ini masih ada perlakuan mengusir dan “menyembelih” sedemikian rupa umat manusia dalam sebuah negara yang dibilang modern. Tragedi kemanusiaan di Bosnia, di Iraq, Afghanistan, dan negara-negara berpenduduk muslim itu ternyata bukan akhir cerita sedih. Kabar penderitaan saudara-saudara kita di Rohingya semula sayup-sayup sejak di tahun 1948, 1962, 1978, 1991, tetapi membuncah santer di 2012, dan menggegerkan masyarakat mondial sepanjang 2016-2017.
Penderitaan yang menorehkan kisah pilu sepilu-pilunya dengan raungan kematian, tangis, dan banjir air mata, justru diukir oleh Penerima Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Sosok yang disebut pejuang demokrasi dan HAM yang tahun 2012 disemati “Mahkotah Terhormat” tersebut, tampak merestui terjadinya pembantaian warga Rohingya. Otoritas pemerintahan Myanmar yang digenggamnya pun terpotret membuka selubung kekejamannya pada anak negerinya sendiri. Melihat sikap membisu Aung San Suu Kyi dalam merespons prahara yang tidak dapat ditoleransi oleh manusia yang beradab itu, mengingatkan saya pada cerpen Mademoiselle Fifi (1882) karya Guy de Maupassant (1850-1893), kita dibuat terhenyak, merenungi kelemahan manusia. Gerakan yang kemudian santer terdengar adalah seruan untuk mencabut hadiah Nobel Perdamaian yang disandangnya.
Saya menyimak penuh makna bahwa terhadap nestapa Rohingnya terdapat berbagai spekulasi dan analisis geopolitik multiperspektif. Latar konflik etnis dan agama menyembul sangat fenomenal di samping problem dominonya perebutan ladang sumber daya. Geoff Hiscock tahun 2012 telah menerbitkan Earth Wars: The Battle for Global Resources. Pertempuran memperebutkan sumber daya global memang menandai terjadinya Perang Bumi. Earth Wars is an attempt to show just how interconnected our world has become in terms of the supply and demand for all sorts of resources, as living standards rice and energy consumption grows in advenced and emerging economic. Pangan, air, energi, dan logam menjadi ladang “palagan baru” yang telah memasuki babak krusial dan sangat ambisius. Selama berabad-abad Barat telah mengontrol sebagian besar aliran sumber daya, dan kini harus waspada, karena China, India, Turki, Rusia, Brazil, Iran, maupun Indonesia sedang menagih bagiannya.
Tulisan ini tentu tidak hendak terus mengusik apa yang sudah berisik, tetapi sedikit memberikan permenungan untuk menyarikan inti perjalanan. Tragedi pengusiran sejatinya adalah lambang dinamik peradaban manusia untuk menemukan kematangan dalam menggapai kehidupan. Selama 350 tahun rasa penat dan lelah telah dijalani Umat Islam Nusantara dalam menghadapi penjajahan kaum imperalis Barat (Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, maupun Jepang). Bangsa Indonesia telah lulus uji penderitaan untuk meniti “jembatan emas kemerdekaan”.
Sejarah peralihan peradaban surgawi ke ruang duniawi di Bumi ini pun adalah bagian dari konstalasi pengusiran manusia sesuai dengan nalar takdirnya. Dalam Alquran dapat dirujuk beragam ayat mengenai posisi penting manusia sebagai pemimpin di Bumi, khalifa fil ard, bukan untuk menjadi khalifah di Surga. Maka penempatan awal penciptaan Nabi Adam AS adalah bagian dari tapak panjang yang meretas langkah historis Surga ke Dunia yang fana ini.
Berbagai skenario dan pelajaran hidup diberikan oleh Allah SWT sampai pada tingkatan transformasi ilmu yang langsung di ajarkan Allah SWT kepada Nabi Adam AS yang “diviralkan” kepada para malaikat. Nabi Adam AS menjadi ilmuwan yang mampu mengajarkan arti hidup dan benda-benda yang fenomenal maupun kodrati dengan persaksian malaikat serta mahkluk-makhluk lain di Surga. Tetapi itu bukanlah habitat permanen Nabi Adam AS sebagai manusia dengan puncak kisahnya yang sangat dramatik dengan dipersilakannya Nabi Adam AS beserta Ibunda Hawwa untuk “bermuhibah” ke Bumi. QS Albaqarah ayat 38 merekam “peta jelajah” dengan sangat terang: “qulnahbithuu min-haa jamii’aa, fa immaa ya’toyannakum minnii hudan fa man tabi’a hudaaya fa laa khoufun ‘alaihim wa laa hum yahzanuun – Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.
Beribu pemikiran insani tidak akan cukup untuk mampu menerangkan secara persis rumusan yang sangat presisif dan berkebenaran itu dalam deret waktu kehidupan manusia. Ada hal yang dapat dipelajari bahwa sesungguhnya sejak pada mulanya sejarah pengurisan itu dimulai dalam rangka mendewasakan manusia menemukan “petunjuk-Nya”. Ada romantika kedewasaan untuk menggapai petunjuk Tuhan dengan beragam berikhtiar. Kisah Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Isa AS, maupun Nabi Muhammad SAW tidak ada yang luput dari “kisah pengusiran” yang dalam terminologi paling kondusif dinamakan “hijrah”. Berjuta argumen dapat dihadirkan mengenai hijrah dan pengusian agar saling berkelindan membangun lazuardi antara derita dan bahagia.
Dalam lingkup paling kecil adalah suatu tatanan bahwa setiap anggota keluarga kita sendiri harus menerima takdirnya dalam rute yang dituntun oleh roda hidupnya untuk keliling mencari petunjuk Tuhan. Pencarian itu dengan cara berhijrah secara sukarela maupun terpaksa tetapi dengan keteguhan iman. Hanya hijrah atau pengusiran maupun keterusiran sajalah yang pada dasarnya adalah gerakan mematangkan jiwa. Derita dalam perjalanan untuk menempuh jalan keterusiran dari zona nyaman menuju hari-hari yang menawarkan kemungkinan-kemungkinan surgawi adalah setinggi-tingginya penjelajahan iman.
Untuk itulah permaknai dengan keteguhan iman setiap keterusiran itu dari apa yang telah mapan menuju penggapaian-penggapian derajat tertinggi-Nya. Hijrah diajarkan sejak dari Nabi Adam AS dari Surga menuju Bumi yang mendunia, atau lelakon Hijrah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, semua itu merupakan tanda-tanda Sang Kuasa memperjalankan hamba-Nya. Bukankah hanya setelah menempuh jalan Hijrah, terjadi peristiwa Fatkhul Makkah? Kemengan Rasulullah di tanah kelahirannya itu di warnai dengan “drama pengusiran”. Sampai pada tahapan ini, berdamai dengan kesadaran atas peristiwa keterusiran adalah puncak penataan diri dalam menggapai kembali penundukan asal muasal secara gemilang.
Nabi Nuh mengalami keterusiran melalui banjir bandang yang dalam bahasa kekinian adalah bencana alam. Ingatlah bahwa bencana alam terus bergulir menerpa dengan kerugian ekonomi, sosial budaya dan lingkungan pada tingkatan yang memilukan. Peristiwa itu semakin melengkapi deret luka kemanusiaan yang tertorehkan, dan mengusir warga dari tanah kelahirannya. Ingatlah pula kasus Lumpur di Sidoarjo. Bahkan setiap musim penghujan, bukankah ada penanda lonceng kebanjiran sedang dibunyikan untuk diterima sebagai lagu semesta. Sementara dikala monggso ketigo (kemarau), kita semua diwanti untuk mafhum bahwa kekeringan adalah cobaan yang harus diterima dengan penuh tawakal.
Maka bencana yang terjadi rutin setiap tahun cukuplah dianggap sebagai ritual ekologis-klimatologis yang sudah senyatanya ditakdirkan. Belum lagi soal bahaya narkoba, terorisme, konflik antarkampung, tawuran supporter bola, radikalisme maupun LGBT yang semakin marak. Seluruh sendi dan titik kosmis negara ini sepertinya sedang bercerita begitu gamblang mengenai bencana yang mengusir jiwa-jiwa yang rendah iman. Dengarlah suara lirih jiwa-jiwa kita sekarang ini, nyaris banyak yang terusir dari ajaran para Nabi dengan dikangkangi modernitas yang terkadang dianggap suci, meski dia menajisi hati nurani. Agar jiwa-jiwa kita tidak terusir dari petunjuk-Nya, hanya iman yang sepatutnya digondeli, dan kini sambil istirah dengarlah tembang Tombo Ati.